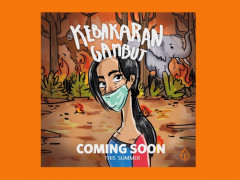Tantangan Pengembangan Ekowisata Gambut Pematang Rahim
Oleh Yitno Suprapto
Putih Yang Tidak Baik

Tak ada lagi hutan lebat sebagai habitat berbagai flora dan fauna yang aman dari perusakan dan eksploitasi berlebihan. Yang tersisa hanyalah lahan basah bagi orang-orang kaya untuk lebih memperkaya dirinya. Ini tercermin dari adanya 3,3 juta hektar perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan. Memperparah keadaan ini, pemerintah justru berusaha untuk melakukan pemutihan terhadap perusahaan-perusahaan pemilik perkebunan itu dengan pasal 110a dan 110b Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Pemutihan adalah upaya pengampunan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan. Dengan kata lain, perkebunan yang awalnya ilegal diubah menjadi legal hanya dengan memenuhi persyaratan serta membayar denda administrasi.
Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Perkebunan sawit ilegal tersebut beroperasi di dalam kawasan hutan yang tersebar pada tiga kategori kawasan hutan dengan fungsi berbeda-beda, yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Dari ketiga kategori, hanya kawasan hutan produksi yang boleh menjadi tempat produksi. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, komersialisasi di kawasan hutan konservasi tidak bisa dilakukan karena merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati tingkat tinggi, termasuk flora fauna yang dilindungi. Hal yang sama juga tidak bisa dilakukan di kawasan hutan lindung karena ia berfungsi sebagai kawasan serapan air dan penyangga bagi wilayah lain—khususnya wilayah konservasi.
Berdasarkan laporan dari Greenpeace dan The Treemap (2019), ada perkebunan kelapa sawit dengan luas lebih dari 100 ha yang tersebar di 49 kawasan konservasi di Indonesia. Secara lebih spesifik, perkebunan tersebut beroperasi di Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan bahkan situs UNESCO. Hal ini bisa mengancam berbagai keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem di kawasan hutan yang selama ini dilindungi oleh undang-undang.
Selain itu, juga ada 278 perusahaan sawit yang beroperasi secara ilegal di area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa 44 persen di antaranya berada di fungsi ekosistem lindung gambut. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 21 PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dimana aktivitas komersial tidak bisa dilakukan di kawasan fungsi lindung ekosistem gambut. Kawasan tersebut memiliki fungsi penting dalam ekosistem hidrologis gambut yang juga merupakan rumah bagi berbagai keanekaragaman hayati.
Tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, kondisi ini juga memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pantau Gambut mengenai karhutla, ditemukan 3 dari 10 perusahaan perusahaan di area KHG yang masuk dalam skema pemutihan berada pada tingkat kerentanan karhutla tinggi (high risk) sedangkan 7 dari 10 persen lainnya berada pada tingkat kerentanan karhutla sedang (medium risk). Dengan kata lain, semua perusahaan yang akan diputihkan rentan terbakar. Alih-alih memperbaiki ekosistem gambut dan mencegah karhutla berikutnya terjadi, pemerintah justru memilih untuk mengampuni perusahaan-perusahaan itu.
Tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, pemutihan ini juga memberikan kerugian keuangan pada negara. TuK INDONESIA melakukan analisis di Kalimantan Tengah terkait potensi kerugian negara melalui perbandingan antara target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dengan yang sebenarnya tercapai. Berdasarkan analisis tersebut, ada perbedaan sebesar kurang lebih Rp4,6 Triliun antara potensi penerimaan pendapatan di sektor sawit dengan realisasi pendapatan pajak daerah di seluruh sektor.
Masyarakat lokal juga bisa menjadi korban dengan kehadiran perkebunan-perkebunan ilegal tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya proses konsultasi transparan dan bertanggung jawab oleh perusahaan terhadap masyarakat lokal. Contoh paling aktual adalah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga Desa Bangkal di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada awal bulan Oktober 2023. Masalah ini berakar dari konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (PT. HMBP). Absennya proses konsultasi itu mengindikasikan perkebunan sawit yang beroperasi tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Dalam perizinan tersebut, perusahaan seharusnya melakukan konsultasi dengan masyarakat lokal dengan mengedepankan prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent). Ini adalah hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap berbagai hal yang akan mempengaruhi tanah, wilayah, dan hak mereka.
Masalah tidak sampai di situ. Perusahaan-perusahaan dengan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) juga ditemukan beroperasi secara ilegal misalnya PT. HMBP. Temuan ini tentu bertolak belakang dengan tujuan utama ISPO, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan penerimaan pasar internasional terhadap minyak kelapa sawit Indonesia, sesuai dengan Pasal 3(b) dan 3(c) Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dengan kata lain, perusahaan hanya melakukan greenwashing untuk memenuhi ketentuan prosedural.
Di sisi lain, juga ada kontradiksi dalam kebijakan pemutihan sawit. Dalam UU P3H. ada sanksi pidana bagi pelanggaran pasal 92 terkait kegiatan perkebunan di atas hutan tanpa izin menteri. Akan tetapi, aturan tersebut menjadi tidak berlaku akibat hadirnya Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) pasal 110a dan 110b yang lebih mengutamakan sanksi administrasi. Padahal, ketentuan dalam UU P3H tidak menerapkan asas ultimum remedium–hukum pidana sebagai upaya terakhir penegakan hukum, dengan menempuh jalur hukum lain terlebih dahulu selain pidana–sehingga seharusnya sanksi pidana terhadap entitas yang melanggar tidak ditiadakan.
Di samping itu antara Pasal 110a UUCK dengan peraturan pelaksananya, yakni PP No. 24 Tahun 2021, juga terdapat perbedaan frasa mengenai tenggat waktu penyelesaian. Ini akan berimplikasi pada rancunya implementasi norma. Pada Pasal 110a UUCK disebutkan bahwa tenggat waktu 2 November 2023 adalah untuk menyelesaikan persyaratan perizinan, sedangkan pada Pasal 19 PP No. 24/2021 disebutkan bahwa batas waktu tiga tahun sejak berlakunya UUCK No. 11/2020 adalah untuk pengajuan permohonan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi batas waktu bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan penyelesaian perizinan perkebunan di kawasan hutan.
Berbagai kontradiksi ini menjadi sebuah anomali yang menjadi celah dan alat untuk mengampuni pelanggaran-pelanggaran yang sudah dan akan terjadi. Proses eksekusi putusan karhutla yang hingga kini belum tuntas juga akan terdampak implementasinya oleh hadirnya kebijakan ini. Pada akhirnya, alam dan masyarakatlah yang menjadi korban.
Melihat dampak luar biasa dari keputusan pemerintah ini, Pantau Gambut berupaya untuk menyajikan informasi mengenai pemutihan melalui cara yang lebih mudah dimengerti. Dengan tajuk #PerburuanMonsterPutih Pantau Gambut menghadirkan sebuah permainan yang mengajak publik untuk bermain sekaligus memahami seputar pemutihan. Langkah yang dipilih oleh pemain akan menentukan jalan cerita dalam Perburuan Monster Putih. Ayo bergabung dengan kami dalam perburuan ini melalui tautan berikut!