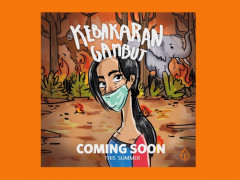Belajar Mengolah Gambut dari Para Transmigran di Ogan Komering Ilir
Oleh Simpul Jaringan Sumatra SelatanSagu Sentani: Dari Bahan Pangan Hingga ‘Mas Kawin’

Bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran Danau Sentani, tiada hari tanpa mengkonsumsi papeda yang terbuat dari pati sagu. Namun, bagi mereka, tanaman sagu lebih dari sekadar urusan perut, tapi juga soal identitas, pembagian wilayah kesukuan, upaya menjaga lingkungan, dan budaya matrimonial. Kearifan lokal turun temurun ini masih dipraktikkan hingga sekarang, meskipun sudah mulai tergerus zaman.
Warga Desa Yoboy, Distrik Sentani, Jayapura, Papua, punya cara sendiri untuk mengambil adonan papeda dari sempe (mangkok yang terbuat dari tanah liat) ke piring. Bagi para perempuan, lazimnya mereka akan mengambil papeda hanya dengan satu garpu bambu atau hiloi yang diputar-putar dengan satu tangan. Akan tetapi, bagi para laki-laki, mereka mengambil papeda dengan dua hiloi, masing-masing satu di tangan kanan dan kiri. Tentunya, jauh lebih mudah mengambil adonan papeda yang kental dengan dua hiloi.
“Kalau tidak bisa putar papeda seperti saya ini, pasti bukan perempuan Sentani,” ujar Debora Wally-Tokoro, salah satu warga Yoboy, sambil mempraktikkan bagaimana mengambil papeda dengan satu hiloi, memutar adonan, dan menuangnya di piring makan.
Sambil mengambil gulungan papeda baru untuk piring berikutnya, mama Debora mulai bercerita bagaimana warga Yoboy sudah turun-temurun bergantung kepada sagu. Warga Yoboy memiliki budaya bahwa seorang suami akan harus melakukan tokok (tebang) pohon sagu ketika istrinya mengandung 6 bulan agar terdapat jaminan pangan ketika nanti kelahiran tiba. Dengan cara penyimpanan yang baik, pati sagu dapat bertahan hingga berbulan-bulan.
Alasan lainnya adalah dalam periode 3 bulan dari periode tokok hingga kandungan usia 9 bulan, sisa batang sagu akan membusuk dan akan banyak terdapat ulat sagu. Ulat sagu ini bisa menjadi sumber protein bagi ibu setelah melahirkan.
“Itu masih sering dilakukan. Meskipun orang tokok juga sagu bisa kapan saja, karena untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Itu sebabnya tanaman yang di pinggir-pinggir desa ini sudah semakin jarang,” kata Debora.
Di pinggiran Danu Sentani, Desa Yoboy memiliki hamparan tanah bergambut yang sangat cocok sebagai tempat tumbuh pohon sagu. Warga sendiri sebenarnya kurang familiar dengan istilah lahan gambut. Mereka lebih mengenal tanah jenis ini sebagai tanah atau lumpur hidup.
Warga Yoboy menyebut lokasi tumbuh sagu ini sebagai ‘dusun’. Tiap-tiap suku memiliki dusun masing-masing yang dibagi secara adat. Di Yoboy sendiri terdapat lima suku dengan lima marga, yaitu Tokoro, Wally, Yom, Sokoy, dan Depondoye. Tiap-tiap suku juga hanya boleh menebang sagu miliki marga mereka. Menebang tanaman sagu milik marga lain diperbolehkan jika di antara mereka memiliki hubungan kekerabatan atau pernikahan. Misalnya saja, salah satu marga Tokoro boleh meminta izin menebang sagu keluarga Wally karena ada salah satu marga Wally yang telah menikah dengan anggota Tokoro.
Selain urusan tebang-menebang, tanaman sagu juga berperan penting bagi pasangan antar keluarga atau antar desa yang ingin membangun rumah tangga. Salah satu tanaman sagu yang dianggap penting ini adalah varian sagu duri, atau secara ilmiah dikenal dengan nama Matroxylon rumphii. Seperti namanya, pohon sagu varian ini memiliki duri di seluruh batangnya. Sehingga, secara teknis, menebang sagu duri lebih sulit dilakukan dan memerlukan banyak orang.
Dalam bahasa lokal, sagu duri ini disebut ‘para’.
“Kalau mau tokok (menebang) sagu para, harus minta izin kepala suku. Kami tokok sagu para buat anak perempuan,” kata Naftali Felle, kepala suku marga Felle di Desa Atabar, Distrik Ebungfaw.
Desa Atabar atau Abar juga merupakan salah satu desa di pinggiran Danau Sentani di Jayapura, Papua. Meskipun berbeda distrik, Yoboy dan Abar bisa dijangkau dengan sekitar 20 menit perjalanan perahu. Seperti Yoboy, Abar juga memiliki sejumlah daerah bergambut di pinggiran danau dengan tanaman sagu yang tumbuh subur.
Menurut Naftali, jika ada anak perempuan dari desanya akan menikah dengan orang dari luar desa tersebut, maka keluarganya akan menebang sagu. Pati dari tanaman sagu itu nantinya akan menjadi hantaran keluarga perempuan ke besan mereka. Pohon sagu para ini dipilih karena biasanya menghasilkan pati dalam jumlah yang lebih banyak dibanding varian lain, seperti sagu yepha atau folo. Dengan pati yang banyak, maka akan lebih banyak papeda yang bisa disajikan untuk keluarga baru tersebut.
Jumlah pati sagu yang dihasilkan berbeda-beda antara tanaman. Untuk pohon sagu dengan tinggi hingga 20 meter, pati yang dihasilkan bisa mencapai 1 ton. Sementara itu, untuk tanaman yang lebih kecil, satu kali tebang sagu bisa menghasilkan sekitar 200 hingga 300 kilogram pati.
“Sagu sangat penting bagi kami. Meskipun kami juga mengonsumsi nasi, agar tidak bosan setiap kali harus makan dengan papeda. Tanah hidup harus harus dijaga agar sagu tumbuh baik,” kata Naftali.
Seperti di Yoboy, kampung Abar juga didiami oleh lima marga, yaitu Felle, Doyapo Bakeho, Ebalkoi, Wally, dan Doyapo Punggauw. Mereka hidup berdampingan dan saling mengingatkan jika ada salah satu yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam menebang sagu.
“Tokok sagu harus benar-benar di bawah (dekat pangkal pohon), agar nanti ada anakan sagu yang tumbuh kemudian,” kata Naftali, menutup ceritanya.